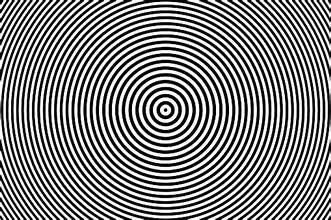“Hidup bukan tentang menghapus semua ilusi, tetapi menyadari bahwa ia ada”
Banyak dari kita menjalani hidup seolah-olah segala sesuatu pasti, tetap, dan dapat dikendalikan. Kita membangun rencana, menumpuk harapan, dan menempelkan makna pada hal-hal yang sesungguhnya rapuh. Tanpa disadari, di sanalah ilusi mulai bekerja—bukan sebagai kebohongan yang disengaja, melainkan sebagai keyakinan yang kita pelihara bersama.
Ilusi pertama adalah anggapan bahwa hidup selalu berjalan sesuai usaha. Kita diajarkan untuk percaya bahwa kerja keras pasti berbuah, kesabaran selalu dibalas, dan kebaikan tidak pernah sia-sia. Padahal kenyataan sering kali meleset. Ada yang bekerja tanpa hasil, ada yang sabar tanpa akhir, ada pula yang baik namun tetap terluka. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, kita menyebutnya ketidakadilan, padahal mungkin yang runtuh adalah ilusi tentang kepastian.
Ilusi berikutnya adalah identitas. Kita mengira diri kita adalah jabatan, peran sosial, gelar, atau pengakuan orang lain. Saat semua itu ada, kita merasa utuh. Saat ia hilang, kita merasa kosong. Padahal identitas-identitas itu hanyalah topeng sementara. Kita lupa bahwa sebelum semua nama dan peran melekat, kita hanyalah manusia yang bernapas, merasa, dan rapuh. Ilusi membuat kita lupa pada hakikat diri.
Ada pula ilusi tentang waktu. Kita hidup seakan-akan masa depan selalu tersedia. Kita menunda hidup dengan alasan “nanti”: nanti bahagia, nanti tenang, nanti bermakna. Hari ini hanya dianggap jembatan. Padahal hidup tidak pernah terjadi di masa depan. Ia selalu berlangsung sekarang. Ketika kita terus menunggu momen ideal, sesungguhnya kita sedang hidup dalam ilusi waktu.
Ilusi juga hadir dalam relasi. Kita berharap orang lain memahami tanpa dijelaskan, setia tanpa diuji, dan selalu hadir sesuai keinginan kita. Kita lupa bahwa setiap orang membawa luka, keterbatasan, dan ketakutannya sendiri. Saat harapan itu runtuh, kita kecewa, marah, dan menyalahkan. Padahal yang pecah bukan cinta, melainkan ilusi tentang kesempurnaan manusia lain.
Namun, hidup dalam ilusi tidak selalu berarti buruk. Ilusi sering menjadi pintu awal perjalanan kesadaran. Ketika ilusi runtuh, kita terluka, tetapi dari sanalah kita mulai melihat lebih jujur. Kita belajar bahwa hidup tidak perlu selalu jelas untuk dijalani, tidak harus pasti untuk dimaknai.
Mungkin kebijaksanaan bukan tentang membangun ilusi baru yang lebih indah, melainkan berani hidup tanpa terlalu bergantung pada ilusi lama. Menerima hidup apa adanya—tidak sepenuhnya terang, tidak selalu adil, namun tetap layak dijalani dengan kesadaran.
Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghapus semua ilusi, tetapi menyadari bahwa ia ada. Kesadaran itulah yang membebaskan kita: dari tuntutan berlebihan, dari harapan yang kaku, dan dari kelelahan untuk menjadi sesuatu yang bukan diri kita. Saat ilusi mulai luruh, hidup tidak menjadi lebih mudah, tetapi menjadi lebih nyata.(D.Wijaya/Gumikbali.co.id)